Apartemen-apartemen baru terus
berdiri di Yogyakarta. Salah satu diantaranya mampir ke mejaku hari Kamis yang
lalu, meminta agar disusunkan strategi pemasaran ciamik agar seluruh unitnya
kandas disikat investor berduit. Ini sebenarnya femonena yang lucu. Sampai
tahun lalu, rata-rata pengembang properti masih sepakat bahwa Yogyakarta yang
rentan gempa, gunung meletus dan tsunami tidak cocok untuk pembangunan
apartemen. Hingga kemudian apartemen Mataram City dibangun dan laku keras,
menginspirasi pengembang lain untuk ikut membangun apartemen/condotel. Asyiknya
lagi, timing apartment-rush di
Yogyakarta ini sangat tepat. Karena pada saat yang bersamaan, Yogyakarta sedang
dijual.
Saya hidup di Yogyakarta selama
empat tahun, dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Kala itu, Yogyakarta masih
sangat nyaman. Yang saya sempat saya saksikan hanyalah awal dari penjualan
Yogyakarta. Seperti pembangunan hotel 'The Rich' (kudos for the best name ever)
yang sepertinya lebih cocok ada di Dubai dibandingkan di Yogyakarta; munculnya
billboard bertajuk studying can be fun yang
mempromosikan apartemen Mataram City pada pelajar (if you need an apartment to make studying fun, go to UI); dan
gonjang-ganjing kecil lainnya.
Seiring waktu berjalan, dibawah
pimpinan walikota baru Haryadi Suyuti (satu-satunya cawalkot yang mendapatkan
dukungan penuh keraton pada pilkada Yogyakarta lalu), Yogyakarta menjadi
semakin sumpek. Beberapa masalah 'karya' Haryadi Suyuti adalah penataan ruang
publik yang buruk; kawasan tepi sungai yang semakin tak terurus; menjamurnya
pembangunan hotel yang membebani lingkungan kota; hingga banyaknya aktivitas
seni budaya yang dihilangkan (Hilal, 2013) .
Dari sekian masalah ini, 'penjualan Yogyakarta' melalui pemberian izin
berlebihan terhadap hotel dan apartemen adalah salah satu yang paling membuat
geram masyarakat. Pasalnya, pembangunan hotel dan apartemen ini kerap merusak
ekosistem, membuat permukaan air tanah turun dan mengakibatkan warga sekitar
mengalami kekeringan. Selain itu, ia juga memunculkan dampak sosial berupa
bertambahnya kesenjangan, kemacetan dan turisme yang unsustainable (later on this).
Menariknya tidak hanya kota
Yogyakarta saja yang dijual. Di lingkup provinsi pun, Daerah Istimewa
Yogyakarta is on sale. Di pesisir
Kulon Progo, Keraton (pemerintah provinsi DIY) dan Bupati Kulon Progo sejak
2006 berusaha gigih untuk merebut kawasan pertanian sepanjang pesisir Kulon
Progo (yang dilindungi oleh UU Agraria) dan merubahnya menjadi kawasan
pertambangan pasir besi. Kasus yang paling terakhir dan paling hits adalah rencana
keraton mengubah logo Yogyakarta menjadi Togua dalam sebuah transaksi fantastis
senilai 1,5 miliar Rupiah! (more on this later)
Hanya tuhan yang tahu berapa persen dari nilai tersebut yang jadi komisi untuk
para 'penanggung jawab'.
Meski kritik dari pegiat seni
terus mengalir deras, tidak ada tanda-tanda Yogyakarta akan mengubah langkah. Mungkin
memang tidak ada kota menggairahkan yang bisa lepas dari cengkraman
kapitalisme. Mungkin memang sudah suratan takdir bagi Yogyakarta untuk berakhir
sebagai sapi perah manusia-manusia serakah. Mungkin memang sudah waktunya bagi
romantisme klasik kota ini untuk usai. Para alumni Yogyakarta seperti saya
mungkin hanya bisa menatap sedih dari jauh, sementara penduduk Yogyakarta
mungkin hanya bisa tetap tunduk pada Keraton dan kepanjangan tangannya yang getol
berjualan.
And the walls kept
tumbling down
In the city that we love
Great clouds roll over the hills
Bringing darkness from above
In the city that we love
Great clouds roll over the hills
Bringing darkness from above
But if you close your
eyes,
Does it almost feel like
Nothing changed at all?
[Bastille - Pompeii]
Does it almost feel like
Nothing changed at all?

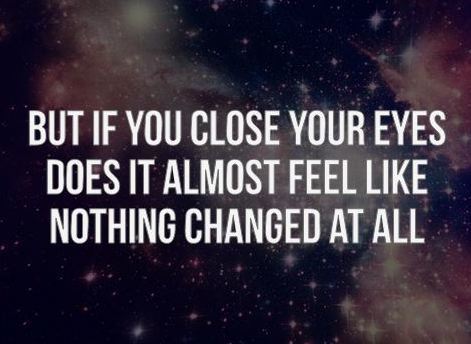

Tidak ada komentar:
Posting Komentar